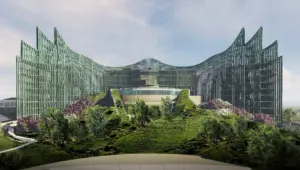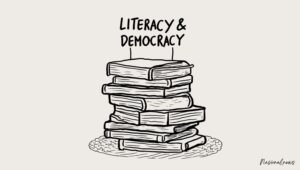KETIKA lonceng tahun ajaran baru berdentang pada 14 Juli 2025, Indonesia memulai sebuah eksperimen pendidikan skala nasional yang belum pernah dilakukan sebelumnya: Sekolah Rakyat.
Sebanyak 100 lokasi Sekolah Rakyat di berbagai provinsi resmi dibuka, menandai tahap pertama dari program besar yang dijanjikan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Namun di balik semangat peluncuran dan barisan data kesiapan yang impresif, muncul pertanyaan-pertanyaan penting, seberapa dalam kesiapan substansi pendidikan ini, dan seberapa jauh keberlanjutan program ini telah dipikirkan?
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian PUPR mencatat bahwa 63 lokasi gelombang pertama (tahap IA) sudah 98,3% rampung, dan 37 lokasi tambahan (tahap IB) akan selesai akhir Juli. Rinciannya meliputi renovasi bangunan lama milik negara, dengan ruang kelas, asrama, perpustakaan, dapur, hingga UKS yang direnovasi dalam waktu singkat.
Kilas data ini terdengar meyakinkan. Tetapi ketika pembangunan disandarkan pada kecepatan semata, kekhawatiran tentang kualitas menjadi sah. Pembangunan yang cepat memang penting untuk mengejar ketertinggalan akses pendidikan.
Namun, tanpa pengawasan mutu yang ketat, sekolah-sekolah ini bisa berubah menjadi bangunan megah tanpa jiwa: berdiri, tetapi tidak hidup.
Apalagi, menurut keterangan Mensos Tri Rismaharini, tahap II akan menyasar 202 lokasi tambahan yang kini masih dalam tahap survei. Bila pengulangan pola “kejar tayang” terjadi, bukan tak mungkin kualitas pengelolaan sekolah justru menurun di fase ekspansi.
Data dari DPR dan Kemensos menunjukkan bahwa 9.755 siswa akan mengikuti program ini, tersebar dalam 256 rombongan belajar, dari SD hingga SMA. Mereka direkrut bukan berdasarkan nilai akademik, melainkan pada basis desil ekonomi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk afirmasi. Tapi di balik itu, muncul tantangan besar, siapa yang akan membimbing ribuan anak ini?
Sekitar 1.500 guru dan 3.390 tenaga kependidikan memang sudah direkrut. Namun, tidak ada jaminan mereka semua akan bertahan di lokasi-lokasi terpencil, dengan fasilitas terbatas, dan beban kerja tinggi. Tanpa sistem insentif dan pelatihan berkelanjutan, potensi tingginya angka turnover akan menggerus kualitas pembelajaran sejak awal.
Kurikulum yang disiapkan secara kolaboratif antara Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemensos memang menawarkan pendekatan boarding, deep learning, serta multi-entry–multi-exit. Namun narasi indah itu akan gugur bila para pengajar tidak memiliki kapasitas atau tidak betah tinggal di lokasi pengabdian.
Sekolah atau Shelter Sosial?
Yang juga patut dikritisi adalah narasi “pendidikan berasrama” yang disebut sebagai jalan keluar untuk kemiskinan.
Sekolah Rakyat didesain mirip pesantren atau boarding school, lengkap dengan bimbingan karakter dan kegiatan spiritual. Tapi apakah ini bentuk pendidikan emansipatif, atau sekadar penitipan massal bagi anak-anak miskin?
Anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 bukan sekadar angka statistik di depan mata. Mereka adalah manusia dengan hak atas pendidikan berkualitas, bukan sekadar tempat tidur, dapur, dan ruang belajar.
Bila sistem pengasuhan dan pendekatan kurikulum tidak mampu menyentuh sisi kemanusiaan mereka secara utuh, maka risiko psikososial yang ditanggung anak-anak ini dalam jangka panjang justru akan lebih besar.
Dalam perspektif ini, Sekolah Rakyat bisa jadi terlalu banyak mengurus hal teknis, tetapi belum cukup memikirkan aspek keberlangsungan hidup muridnya seperti bagaimana kelak mereka mengakses universitas? Apakah ada program alumni? Bagaimana dengan penguatan soft skill?
Dengan anggaran awal sekitar Rp1 triliun untuk 100 lokasi tahap pertama, program ini tergolong masif dan ambisius. Tapi perlu diingat, itu baru tahap awal.
Bila benar 202 lokasi tambahan akan dibuka dan seluruh sarana harus dibangun permanen mulai 2026, maka pemerintah harus bersiap menggelontorkan dana multiyears dalam skala besar.
Pertanyaannya, apakah APBN siap? Lebih jauh, apakah prioritas ini akan terus berlanjut jika terjadi pergantian kebijakan, menteri, atau kepentingan politik?
Kondisi inilah yang membuat Sekolah Rakyat sangat rentan menjadi program jangka pendek berbiaya besar, tanpa jaminan keberlanjutan.
Sejarah pendidikan Indonesia sudah mencatat banyak proyek pendidikan yang gagal bertahan lebih dari dua tahun karena perubahan arah politik atau ketiadaan dukungan anggaran lanjutan.
Dari Eksperimen ke Sistem
Program Sekolah Rakyat adalah eksperimen berani yang dimulai dengan niat baik. Ia menyasar kelompok paling rentan, menciptakan ruang pendidikan baru, dan memberi harapan bagi anak-anak yang selama ini tak terjangkau.
Namun niat baik tidak cukup. Tanpa evaluasi berkelanjutan, keberpihakan terhadap kualitas pengajar, dan jaminan pendanaan jangka panjang, program ini berisiko menjadi proyek kosmetik belaka. Dengan kata lain, bangunannya mungkin berdiri, tetapi pendidikan tidak tumbuh.
Harapan kita adalah Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi proyek percontohan, tetapi menjadi sistem alternatif pendidikan nasional yang tahan uji, berbasis data, manusiawi, dan setara.
Untuk itu, butuh konsistensi, keberanian, dan kemauan politik jangka panjang. Jika tidak, maka Sekolah Rakyat hanya akan menjadi sekolah yang ramai di awal, lalu dilupakan ketika sorotan meredup.
EDITORIAL NASIONAL.NEWS