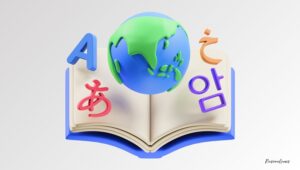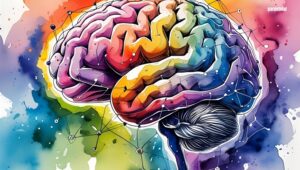PUBLIK dibuat terkejut oleh respons keras sejumlah partai politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.
Putusan ini pada dasarnya membawa konsekuensi struktural terhadap penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia.
Namun, reaksi keras parpol justru memunculkan pertanyaan mendalam, apakah ini soal prinsip demokrasi, atau sekadar resistensi terhadap perubahan yang tidak menguntungkan secara politis?
Sikap partai-partai besar menunjukkan spektrum tanggapan yang beragam. Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan, menolak putusan tersebut dengan dalih menciptakan deadlock konstitusional.
Djarot bahkan menyerukan agar putusan MK dimoratorium dan diserahkan kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Artinya, putusan MK diposisikan sebagai permulaan deliberasi, bukan sebagai akhir dari proses konstitusional, yang sejatinya tidak sesuai dengan prinsip dasar sistem hukum kita.
Sementara itu, Dradjad Wibowo dari PAN juga menyatakan keraguannya atas kelayakan keputusan ini. Baginya, pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah merupakan langkah yang layak dipertanyakan.
Namun ia tidak memberikan rincian konseptual yang menjelaskan secara hukum, apakah yang dipermasalahkan adalah muatan keputusannya atau wewenang MK dalam memutuskan hal tersebut.
Di sisi lain, Mardani Ali Sera dari PKS memberikan narasi yang lebih reflektif. Ia menyatakan bahwa pemisahan pemilu justru bisa meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa perhatian publik tidak hanya tersedot ke ranah nasional, tapi juga memberi ruang hidup bagi isu-isu lokal.
“Demokrasi itu untuk rakyat. Demokrasi terbaik yang paling sesuai dengan kondisi rakyat,” ujar Mardani.
Mardani melihat bahwa penyatuan pemilu nasional dan lokal telah menimbulkan dominasi narasi nasional yang memarginalkan kepentingan daerah.
Finalitas dan Sifat Mengikat Putusan MK
Satu hal yang tidak dapat diperdebatkan dalam kerangka hukum tata negara adalah bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.
Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan terakhir.
Tidak ada jalur banding, tidak ada ruang kasasi. Sejak diucapkan, putusan MK otomatis memiliki kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya jelas, tidak ada prosedur hukum yang sah untuk mengubah, menggugat, apalagi membatalkan putusan MK.
Oleh karena itu, resistensi parpol terhadap keputusan ini harus dibaca secara politis, bukan legal.
Dan, justru di sinilah terjadi kontradiksi, bahwa partai-partai yang notabene menjadi produk dari demokrasi konstitusional justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan semangat konstitusionalisme itu sendiri.
Antara Finalitas Hukum dan Kekuasaan Politik
Ditengah polemik ini, Mahfud MD, mantan Ketua MK, muncul memberikan pernyataan yang penting dicermati.
“Kita harus bersifat konstitusionalistik. Putusan MK itu mengikat. Itu harus dilaksanakan… Gimana, sih, kalau DPR-nya enggak mau? Enggak bisa. Wajib dilaksanakan,” ujarnya seperti diberitakan kompas.id.
Secara implisit, Mahfud MD mengingatkan bahwa dalam negara hukum, tidak boleh ada aktor politik, termasuk DPR, yang imun terhadap konstitusi.
Namun Mahfud juga memberi catatan tajam, bahwa dalam kasus ini, MK telah menyentuh wilayah open legal policy, yakni kebijakan yang seharusnya ditentukan oleh pembentuk undang-undang, bukan oleh pengadilan.
Dengan kata lain, MK dituding telah melampaui batas kewenangannya, khususnya dalam hal menjadwal pemilu.
Tuduhan ini bukan tanpa dasar. Dalam teori hukum tata negara, pengadilan konstitusi sejatinya hanya menguji dan menafsirkan norma, bukan merancang teknis pelaksanaannya, terlebih dalam hal yang bersifat administratif seperti penjadwalan. Di sinilah letak ketegangan antara supremasi hukum dan supremasi politik.
Reaksi Parpol
Di balik berbagai pernyataan publik yang bernada normatif, perlu dipertanyakan secara jernih, apakah sikap parpol merupakan bentuk perjuangan terhadap nilai-nilai demokrasi, atau justru reaksi atas potensi kehilangan kendali politik akibat perubahan arsitektur pemilu?
Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal pada dasarnya memperbesar kemungkinan narasi lokal memperoleh tempat dalam kontestasi elektoral.
Selama ini, penyatuan pemilu menjadikan pemilu lokal sekadar pelengkap, seringkali dikendalikan sepenuhnya oleh isu-isu dan tokoh-tokoh nasional.
Maka, dari sudut pandang masyarakat sipil, pemisahan ini dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan demokrasi daerah dan desentralisasi politik.
Namun bagi parpol besar, fragmentasi pemilu ini bisa mengurangi efisiensi mobilisasi politik, meningkatkan biaya kampanye, serta menyulitkan konsolidasi kekuasaan. Ini bukan soal demokrasi atau konstitusi, melainkan soal kalkulasi elektoral.
Menanti Kepatuhan Konstitusional
Akhirnya, yang diuji bukan hanya logika hukum, tetapi juga integritas politik. Apakah partai-partai politik bersedia tunduk pada prinsip finalitas hukum yang dijamin konstitusi, atau akan terus mencari celah untuk mempertahankan status quo?
Sebagaimana disinggung di awal, waktu akan menjernihkan segalanya. Dalam sistem demokrasi yang sehat, semua pihak harus menerima bahwa hukum adalah pengendali kekuasaan, bukan sebaliknya. Maka, jika MK telah memutuskan, tidak ada pilihan lain selain melaksanakannya.
Namun catatan Mahfud tidak boleh diabaikan. Jika MK mulai memasuki wilayah kebijakan teknis dan administratif, maka ke depan perlu ada penguatan mekanisme pengawasan internal dan etik, agar MK tidak kehilangan kepercayaan sebagai penjaga konstitusi.
Dalam ketegangan ini, kita tidak hanya menyaksikan tarik-menarik antara hukum dan politik, tapi juga ujian atas kedewasaan demokrasi Indonesia.[]
*) Imam Nawawi, penulis adalah Direktur Progressive Studies & Empowerment Center (Prospect)