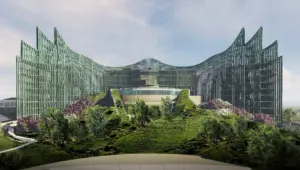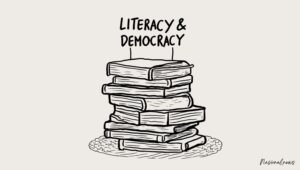AL QUR’AN tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif-religius, melainkan juga sebagai sumber refleksi akademik yang kaya dengan dimensi filosofis, sosiologis, dan politis.
Salah satu potret dialog kritis yang memuat dimensi tersebut dapat ditemukan dalam Surah Asy-Syu‘ara ayat 23–26. Pada rangkaian ayat ini digambarkan interaksi antara Nabi Musa dan Fir‘aun, seorang penguasa otoriter Mesir Kuno.
Pertanyaan yang diajukan Fir‘aun dan jawaban yang diberikan Musa menyimpan nilai epistemologis yang melampaui sekadar perdebatan teologis.
Disinilah kiranya pentingnya teks suci tidak hanya dipahami sebagai doktrin keagamaan, melainkan juga sebagai wacana kritis yang relevan dengan konteks kontemporer, terutama dalam menghadapi otoritarianisme dan manipulasi wacana publik.
Ayat 23 menampilkan pertanyaan Fir‘aun kepada Musa: “Siapakah Tuhan semesta alam itu?” Pertanyaan ini secara lahiriah tampak sederhana, tetapi memiliki makna retoris.
Fir‘aun tidak sedang mencari pengetahuan baru, melainkan berusaha meruntuhkan otoritas Musa di hadapan khalayak. Dalam kerangka epistemologi, tindakan ini mencerminkan skeptisisme politis, menggunakan pertanyaan untuk melemahkan legitimasi lawan, bukan untuk memperoleh kebenaran.
Fenomena ini sejajar dengan praktik dalam tradisi politik modern, ketika penguasa mempertanyakan legitimasi moral lawan politik bukan untuk membuka ruang diskusi, tetapi untuk memperkuat dominasi dan mengontrol opini publik. Dengan demikian, ayat ini dapat dipandang sebagai potret abadi tentang cara penguasa menggunakan bahasa untuk mempertahankan kekuasaan.
Jawaban Kosmologis Musa
Sebagai respons, Musa menjawab pada ayat 24: “Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu sekalian mempercayai.”
Jawaban Musa ini bukan sekadar dogma teologis, melainkan sebuah pernyataan kosmologis yang menyentuh inti keberadaan. Musa mengaitkan keberadaan Tuhan dengan keteraturan alam semesta, langit, bumi, dan segala sesuatu di antaranya, sebuah argumen yang dapat diterima secara rasional.
Dalam filsafat ilmu, jawaban Musa merepresentasikan paradigma teosentris yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber segala realitas.
Ia mengajak Fir‘aun dan khalayak untuk menggunakan akal sehat mereka dalam menyadari bahwa keteraturan kosmos tidak mungkin berdiri tanpa Pencipta. Di sini terlihat bahwa wahyu tidak anti-rasio, melainkan justru mengafirmasi rasionalitas manusia.
Publik sebagai Panggung Legitimasi
Berikutnya, pada ayat 25 mencatat reaksi Fir‘aun: “Tidakkah kamu mendengar (apa yang dikatakannya)?”. Kalimat ini menunjukkan bahwa Fir‘aun berusaha mengalihkan fokus dari substansi argumen Musa ke arah penilaian massa.
Alih alih membantah isi jawaban, melainkan ia mengajak audiens menertawakan atau meragukan Musa. Strategi ini dikenal dalam teori komunikasi politik sebagai delegitimasi retoris, yaitu menggeser perdebatan dari wilayah argumentasi ke ranah persepsi publik.
Sosiologi pengetahuan dapat membantu membaca fenomena ini, bahwa penguasa sering kali tidak membantah kebenaran lawan, tetapi menciptakan “realitas sosial” baru melalui wacana.
Fir‘aun ingin agar publik menganggap jawaban Musa sebagai sesuatu yang asing atau absurd, sehingga otoritas Musa terpinggirkan tanpa perlu dipatahkan secara intelektual. Hal ini menggambarkan betapa eratnya hubungan antara kuasa politik dan produksi pengetahuan.
Historisitas dan Universalisme
Menanggapi strategi Fir‘aun, Musa menambahkan argumennya sebagaiaman pada ayat 26: “Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu.” Pernyataan ini setidaknya mengandung dua dimensi penting.
Pertama, universalisme transendental, bahwa Allah adalah Tuhan semua manusia, termasuk Fir‘aun. Tidak ada ruang bagi penguasa untuk mengklaim dirinya sebagai tuhan tandingan.
Kedua, historisitas religius, dimana Musa menegaskan bahwa ajaran tauhid bukanlah hal baru. Ia adalah kesinambungan ajaran yang telah diwariskan nenek moyang, sehingga klaim keilahian Fir‘aun bertentangan dengan tradisi panjang spiritualitas manusia.
Dari perspektif filsafat sejarah, ayat ini menegaskan kesinambungan nilai ketuhanan lintas zaman. Musa menolak narasi ahistoris yang diangkat Fir‘aun untuk melegitimasi dirinya sebagai “tuhan baru”. Dengan kata lain, Musa mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bisa mencabut akar historis iman umat manusia.
Implikasi Etis-Politik
Jika dianalisis lebih lanjut, rangkaian ayat ini memiliki implikasi etis-politik yang penting. Pertama, ia menegaskan keberanian intelektual dalam menghadapi penguasa absolut. Musa tidak gentar menyampaikan kebenaran meski berhadapan dengan risiko besar.
Kedua, ayat ini mengandung kritik terhadap manipulasi retorika yang sering dipakai oleh penguasa otoriter. Fir‘aun tidak bisa membantah argumentasi rasional, maka ia beralih ke strategi memanipulasi opini.
Dalam konteks kontemporer, ayat-ayat ini relevan untuk membaca praktik politik modern, di mana kebenaran sering kali tidak diukur melalui argumen rasional, melainkan oleh kekuatan media dan opini publik yang dikendalikan penguasa atau elit.
Al-Qur’an melalui narasi ini mengingatkan bahwa suara kebenaran harus tetap ditegakkan, meskipun berhadapan dengan dominasi wacana yang menyesatkan.
Dimensi Teologis dan Humanistik
Selain aspek politik, ayat ini juga menyimpan pesan teologis dan humanistik. Musa menampilkan wajah agama yang rasional, kosmologis, dan historis, bukan sekadar dogmatis.
Dengan demikian, agama tidak hadir untuk memutus ruang dialog, melainkan justru memperluasnya. Dialog Musa dan Fir‘aun menggambarkan dinamika iman, akal, dan kekuasaan yang harus selalu diwaspadai dalam sejarah manusia.
Surah Asy-Syu‘ara ayat 23–26 merekam lebih dari sekadar percakapan antara Musa dan Fir‘aun. Ia merupakan potret abadi tentang pertarungan kebenaran dan kemunkaran.
Fir‘aun menampilkan diri sebagai simbol otoritarianisme yang menggunakan retorika untuk membangun legitimasi semu, sementara Musa tampil sebagai simbol keberanian intelektual dan moral yang mendasarkan argumennya pada rasionalitas kosmologis, historisitas religius, dan universalisme ketuhanan.
Refleksi terhadap ayat ini menegaskan beberapa poin penting. Pertama, dialog suci ini menunjukkan pentingnya menggabungkan wahyu dengan rasionalitas. Kedua, ia memperingatkan tentang modus manipulasi kekuasaan yang sering kali menyingkirkan kebenaran demi menjaga dominasi.
Ketiga, ayat ini memberi inspirasi etis bagi setiap zaman bahwa suara kebenaran, meski minoritas dan terpinggirkan, tetap memiliki daya transformasi yang tidak dapat dipadamkan.
Dengan demikian, kitab suci sejatinya tidak hanya menjadi narasi keagamaan, tetapi juga cermin reflektif bagi dinamika sosial-politik dan intelektual umat manusia sepanjang sejarah.