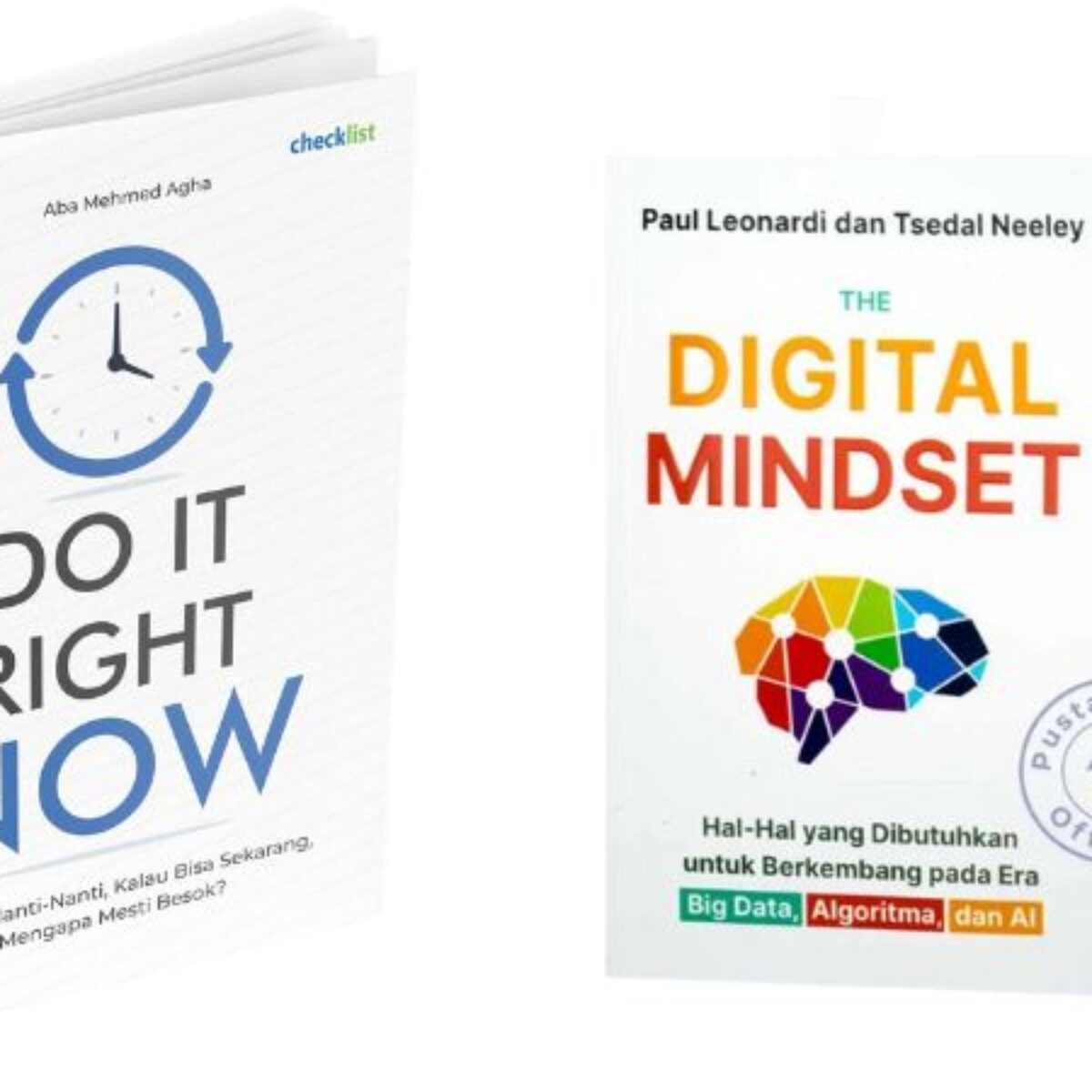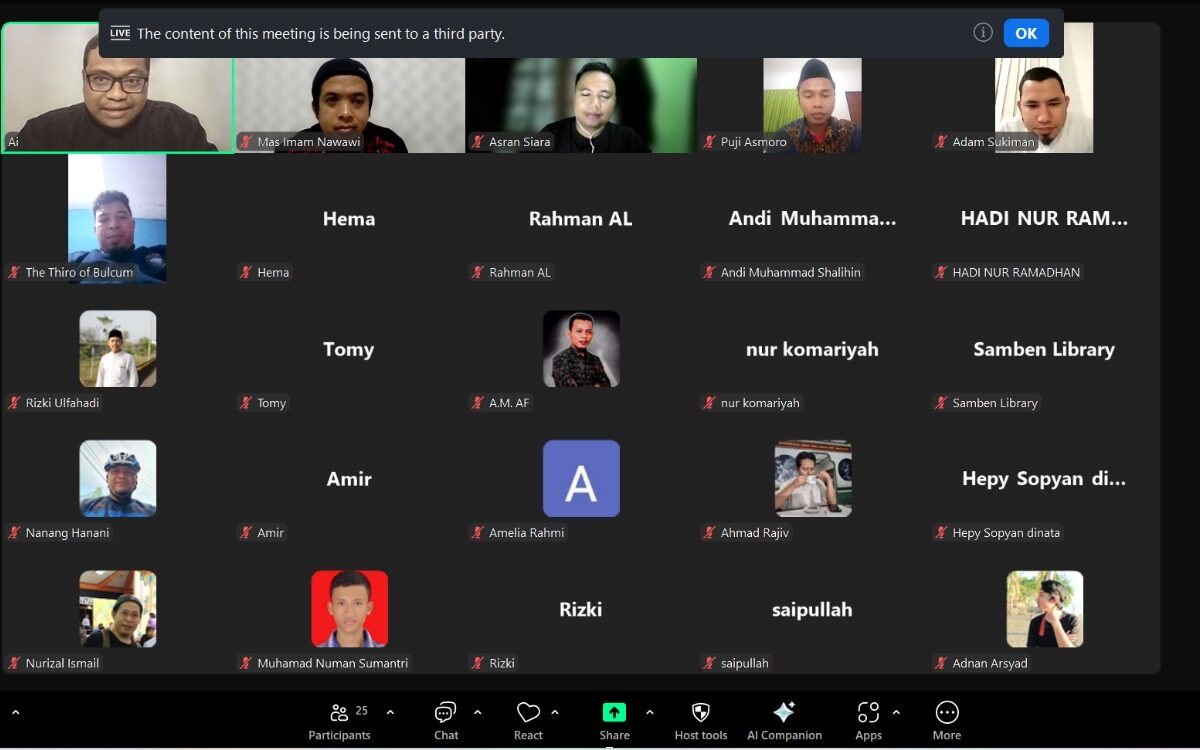Ada satu pernyataan yang kerap kali didengar oleh hampir setiap pelajar di Indonesia, sejak dari bangku sekolah dasar hingga dewasa: “Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun.” Kalimat ini seperti sebuah mantra yang terus diulang-ulang tanpa banyak dipertanyakan. Namun, apakah benar Indonesia dijajah selama itu? Atau, mungkinkah ini hanya salah kaprah yang terlanjur melekat di benak kita?
Bagi mereka yang terbiasa dengan narasi sejarah mainstream, fakta bahwa Indonesia mungkin tidak dijajah selama 350 tahun mungkin mengejutkan. Namun, seperti halnya banyak hal dalam sejarah, kenyataan sering kali lebih rumit daripada apa yang tertulis di buku pelajaran.

Membongkar Mitos: Dari Mana Angka 350 Tahun Berasal?
Mari kita mulai dengan mengurai asal-usul angka 350 tahun ini. Klaim ini biasanya didasarkan pada perhitungan dari tahun 1596, ketika kapal-kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali tiba di perairan Banten, hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 1945. Jika dihitung secara matematis, rentang waktu ini memang sekitar 349 tahun. Namun, apakah penjelajahan pertama Belanda di Nusantara sudah bisa dianggap sebagai permulaan penjajahan?
Saat De Houtman menginjakkan kakinya di Nusantara, apa yang dia temukan bukanlah sebuah bangsa yang tunduk di bawah kekuasaan asing. Sebaliknya, ia menemukan kerajaan-kerajaan yang kuat dan berdaulat, seperti Kesultanan Banten, Mataram, dan berbagai kerajaan di Sumatra dan Sulawesi. Peristiwa ini lebih tepat disebut sebagai awal dari interaksi perdagangan antara dua dunia yang sangat berbeda, bukan sebagai awal dari penjajahan.
VOC dan Awal Pengaruh Belanda
Jika kita ingin berbicara tentang pengaruh Belanda yang signifikan di Nusantara, kita harus melihat ke tahun 1602, ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) didirikan. VOC adalah perusahaan dagang yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk melakukan perdagangan di Asia, termasuk hak untuk membuat perjanjian, mendirikan benteng, dan bahkan mengangkat pasukan. Ini adalah organisasi yang lebih seperti negara dalam negara, dengan kekuatan militer dan ekonomi yang sangat besar.
VOC berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di sebagian besar wilayah Nusantara, namun dominasi mereka tidak berarti penjajahan dalam pengertian yang kita pahami sekarang. Banyak kerajaan lokal masih memegang kendali atas wilayah mereka, dan hubungan dengan VOC lebih mirip dengan aliansi yang penuh ketegangan dan persaingan.
Contoh paling terkenal adalah Kesultanan Mataram di Jawa, yang selama beberapa dekade berperang melawan VOC. Pada saat itu, pengaruh VOC memang besar, tetapi mereka tidak sepenuhnya menguasai Nusantara. VOC lebih merupakan kekuatan ekonomi yang mencoba mengendalikan perdagangan, bukan sebuah kekuatan kolonial yang menduduki tanah.
VOC Bangkrut dan Pemerintah Hindia Belanda
Seiring waktu, VOC mulai mengalami kemunduran. Korupsi, manajemen yang buruk, dan biaya perang yang tinggi menyebabkan VOC bangkrut pada akhir abad ke-18. Pada tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih semua aset VOC dan mendirikan apa yang dikenal sebagai Hindia Belanda.
Namun, sekali lagi, menyebut periode ini sebagai masa penjajahan selama 350 tahun masih menyesatkan. Pemerintah kolonial Belanda yang baru dibentuk masih menghadapi perlawanan dari berbagai kerajaan lokal. Misalnya, di awal abad ke-19, Perang Diponegoro meletus di Jawa, perang yang berlangsung selama lima tahun dan merupakan salah satu perang paling mahal dan berdarah bagi Belanda.
Selain itu, banyak wilayah di luar Jawa, seperti Aceh dan Bali, tetap otonom dan tidak berada di bawah kendali Belanda hingga akhir abad ke-19. Ini menunjukkan bahwa hingga saat itu, “penjajahan” yang dimaksud masih jauh dari mencakup seluruh wilayah Indonesia seperti yang kita pahami sekarang.
Fase Penjajahan yang Sesungguhnya: Abad ke-19 dan ke-20
Baru pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Ini sering disebut sebagai fase “penjajahan yang sesungguhnya,” di mana Belanda menerapkan kebijakan politik dan ekonomi yang lebih ketat. Dengan menggunakan strategi militer yang lebih agresif, Belanda berhasil menundukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya otonom, seperti Aceh (setelah perang panjang dari 1873 hingga 1904) dan Bali.
Pada titik inilah, kita dapat berbicara tentang penjajahan dalam pengertian yang lebih utuh. Namun, bahkan dalam periode ini, kekuasaan Belanda tidak sepenuhnya mutlak. Perlawanan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia terus berlanjut, baik dalam bentuk perang gerilya maupun diplomasi politik.
Realitas yang Lebih Kompleks
Jadi, jika kita ingin menempatkan masa penjajahan Belanda dalam konteks yang lebih akurat, kita harus mengakui bahwa penguasaan penuh Belanda atas seluruh wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia tidak terjadi selama 350 tahun penuh. Kekuasaan Belanda di wilayah Nusantara bersifat bertahap, tidak serentak, dan sering kali dihadapi dengan perlawanan yang gigih.
Ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa kita tetap menggunakan angka 350 tahun ini? Jawabannya mungkin terletak pada kebutuhan akan narasi yang sederhana dan mudah diingat. Dalam upaya untuk menyatukan sebuah bangsa yang begitu beragam seperti Indonesia, kisah tentang perjuangan panjang melawan penjajahan mungkin dianggap sebagai alat yang efektif untuk menumbuhkan rasa persatuan.
Namun, sejarah tidak selalu lurus. Ia penuh dengan nuansa dan kontradiksi, dan penting bagi kita untuk mengakui kompleksitas itu. Dengan memahami bahwa penjajahan Belanda tidak berlangsung selama 350 tahun penuh, kita dapat lebih memahami realitas sejarah yang sebenarnya—dan mungkin, menghargai lebih dalam perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk mencapai kemerdekaan.
Mengapa Narasi Ini Terlanjur Melekat?
Salah satu alasan mengapa narasi “350 tahun penjajahan” ini begitu melekat di benak masyarakat Indonesia adalah karena narasi tersebut digunakan secara luas dalam pendidikan formal dan informal. Sejak masa sekolah dasar, anak-anak diajari bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun, tanpa banyak penjelasan lebih lanjut tentang konteks sejarah yang sebenarnya.
Narasi ini juga diperkuat oleh retorika nasionalisme yang berkembang setelah kemerdekaan. Dalam upaya untuk memperkuat semangat kebangsaan, para pemimpin Indonesia pasca-kemerdekaan sering kali mengandalkan kisah-kisah perjuangan yang panjang dan heroik. Angka 350 tahun menjadi semacam simbol penderitaan yang panjang, yang akhirnya diakhiri dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Namun, narasi ini juga membawa risiko. Dengan menyederhanakan sejarah menjadi satu angka, kita berisiko mengabaikan kompleksitas dan dinamika yang sebenarnya terjadi selama periode penjajahan. Misalnya, perjuangan yang dilakukan oleh berbagai suku dan kerajaan di Indonesia pada berbagai waktu dan tempat menjadi terlupakan atau dianggap tidak penting dibandingkan dengan narasi besar “350 tahun penjajahan.”
Dampak Pemahaman yang Salah Kaprah
Pemahaman yang salah tentang lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak hanya berdampak pada cara kita memandang sejarah, tetapi juga pada cara kita memahami identitas nasional kita. Dengan terus-menerus mengulang narasi 350 tahun, ada kecenderungan untuk melihat diri kita sebagai korban dari sebuah kekuatan asing yang tak terkalahkan selama berabad-abad. Ini bisa mengaburkan fakta bahwa banyak wilayah dan masyarakat di Nusantara berhasil mempertahankan otonomi mereka untuk waktu yang lama sebelum akhirnya ditaklukkan.
Selain itu, narasi ini juga mengabaikan peran penting dari berbagai tokoh dan kelompok yang selama berabad-abad melawan dominasi asing, baik itu melalui perlawanan militer, diplomasi, atau upaya menjaga kedaulatan budaya mereka. Misalnya, kerajaan Aceh, yang meskipun akhirnya dikalahkan, mempertahankan kemerdekaannya selama lebih dari 70 tahun setelah VOC pertama kali tiba di Nusantara.
Penjajahan dalam Pengertian yang Lebih Luas
Penting untuk diingat bahwa penjajahan tidak hanya tentang kekuasaan militer atau politik. Penjajahan juga melibatkan dominasi ekonomi, budaya, dan bahkan psikologis. Dalam hal ini, mungkin benar bahwa pengaruh Belanda di Indonesia mulai terasa sejak awal abad ke-17, ketika VOC mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah ini. Namun, ini berbeda dengan penjajahan dalam pengertian yang kita pahami sekarang, yaitu kekuasaan langsung atas tanah dan rakyat.
Dalam pengertian ekonomi, Belanda memang telah lama mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, terutama melalui perdagangan rempah-rempah. Namun, bahkan dalam hal ini, Belanda tidak memiliki monopoli penuh hingga mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah penting seperti Maluku dan Jawa pada abad ke-18.
Dari sisi budaya, penjajahan juga merupakan proses yang kompleks dan tidak selalu satu arah. Meskipun ada upaya dari Belanda untuk menyebarkan budaya mereka di Indonesia, ada juga resistensi dan adaptasi dari masyarakat lokal. Banyak elemen budaya Indonesia yang tetap bertahan atau bahkan berkembang meskipun berada di bawah pengaruh kolonial.
Merombak Pemahaman Kita tentang Sejarah
Dalam meninjau kembali klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa sejarah tidak pernah sesederhana yang sering digambarkan. Narasi tentang penjajahan Belanda selama 350 tahun lebih merupakan mitos yang berkembang daripada fakta sejarah yang akurat.
Dengan menggali lebih dalam ke dalam sejarah kita, kita dapat memahami bahwa penjajahan Belanda di Indonesia adalah proses yang bertahap, penuh konflik, dan tidak merata. Kekuasaan Belanda baru menjadi dominan di seluruh wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia pada akhir abad ke-19, dan bahkan saat itu, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial terus berlanjut hingga abad ke-20.
Mengakui kompleksitas ini tidak berarti mengurangi pentingnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, ini memungkinkan kita untuk lebih menghargai berbagai bentuk perlawanan dan ketahanan yang ditunjukkan oleh nenek moyang kita sepanjang sejarah.
Dengan demikian, alih-alih terus mengulang klaim yang salah, mari kita beralih ke pemahaman yang lebih kaya dan lebih nuansa tentang sejarah kita sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya belajar dari masa lalu, tetapi juga mendapatkan perspektif yang lebih kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik.